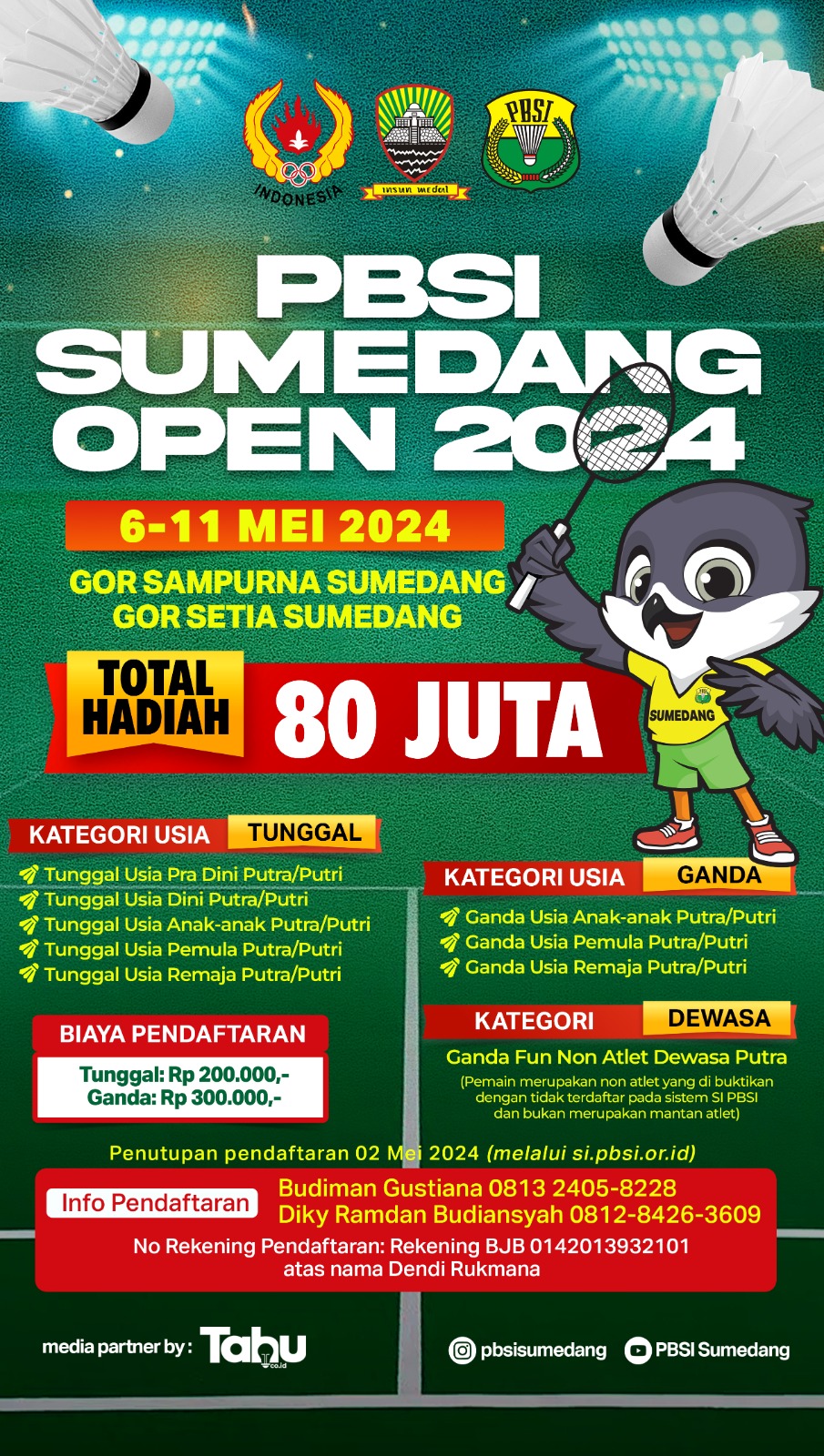Oleh : Annas Fitrah Akbar
Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang viral “Kalau niatnya hanya untuk mencari uang, jangan jadi guru” mengundang reaksi beragam dari masyarakat. Di satu sisi, ucapan ini menegaskan kemuliaan profesi guru. Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai pernyataan tersebut justru melukai hati guru yang berjuang di tengah keterbatasan kesejahteraan. Bagaimana memahami kontroversi ini?
Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) ala Teun A. van Dijk (1997, 2001), kita bisa melihat bahwa pidato Menag bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin ideologi, relasi kuasa, dan kondisi sosial pendidikan di Indonesia.
Guru sebagai Ladang Amal Jariyah
Dalam pidatonya (3 September 2025, UIN Syarif Hidayatullah), Menag menekankan bahwa guru adalah profesi mulia: bukan sekadar pencari nafkah, melainkan pengabdi yang menanam amal jariyah. Pemilihan kata “ladang amal jariyah” menegaskan nuansa religius, mengikat profesi guru dengan dimensi spiritual.
Menurut Van Dijk (1997), strategi ini termasuk dalam semantic moves, yaitu cara pembicara menekankan makna positif agar publik menerima argumen. Dengan menautkan profesi guru dengan pahala, Menag berusaha mengangkat martabat guru secara simbolik.
Realitas Sosial: Guru dan Kesejahteraan
Namun, wacana ini berbenturan dengan kenyataan. Ribuan guru di Indonesia, khususnya guru honorer, masih berjuang dengan gaji minim. Pemerintah memang telah menaikkan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta dan mengangkat 52 ribu guru honorer menjadi PPPK (Detik, 2025). Meski begitu, masalah kesejahteraan masih jauh dari tuntas.
Kritik pun bermunculan. Bagi sebagian guru, kalimat “jangan jadi guru” dianggap menormalisasi penderitaan ekonomi yang mereka alami. Paulo Freire (1970) mengingatkan bahwa sistem pendidikan sering melanggengkan ketidakadilan ketika guru diposisikan hanya sebagai pengabdi, tanpa hak yang layak sebagai pekerja.
Relasi Kuasa dalam Pidato
Pidato Menag menunjukkan relasi kuasa: pejabat negara berhak mendefinisikan “guru ideal” sebagai sosok yang ikhlas, pengabdi, dan tidak materialistis. Namun, dari perspektif AWK, hal ini berpotensi mengaburkan fakta struktural bahwa guru juga berhak atas kesejahteraan.
Fairclough (1995) menyebut fenomena ini sebagai naturalization of discourse, yaitu ketika bahasa pejabat menormalkan suatu kondisi sosial dalam hal ini, gagasan bahwa guru sejati tidak boleh terlalu menuntut materi.
Pidato Menag seharusnya dilihat sebagai momentum untuk mempertegas dua hal:
Pertama, Guru memang profesi mulia. Tidak salah jika ada motivasi spiritual dan pengabdian.
Kedua, Namun guru juga pekerja. Mereka butuh gaji dan tunjangan yang layak agar dapat mengabdi dengan tenang.
Maka, wacana religius tentang “guru sebagai ladang amal jariyah” perlu dilengkapi dengan kebijakan nyata seperti mempercepat pengangkatan honorer, pemerataan tunjangan, dan peningkatan fasilitas pendidikan.
Pidato Menag menunjukkan bagaimana bahasa bisa membentuk realitas sosial. Wacana tentang guru bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal legitimasi, kebijakan, dan nasib jutaan pendidik di Indonesia.
Guru memang panggilan hati. Tapi guru juga manusia yang butuh hidup layak. Keseimbangan antara panggilan mulia dan hak kesejahteraan inilah yang seharusnya menjadi arah kebijakan pendidikan kita.
Daftar Pustaka
Detik.com. (3 September 2025). Sebut Kalau Mau Cari Uang Jangan Jadi Guru, Menag Minta Maaf.
Tempo.co. (4 September 2025). Menteri Agama Minta Maaf Usai Ucapan Soal Guru Viral.
Kumparan.com. (3 September 2025). Menag Sebut Guru Profesi Mulia, Kalau Cari Uang Jangan Jadi Guru.
Van Dijk, T. A. (1997). Discourse as Structure and Process. London: Sage.
Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. London: Longman.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.